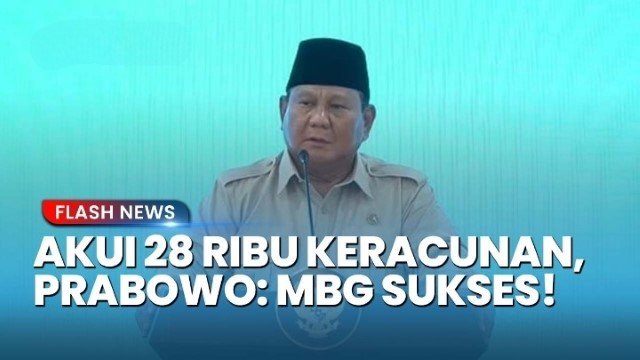Korupsi Whoosh dan Ujian Moral Negara: Tangkap Jokowi dan Luhut!

Korupsi Whoosh dan Ujian Moral Negara Tangkap Jokowi dan Luhut!
SETAHUN setelah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung resmi beroperasi, suara yang paling nyaring bukan deru mesinnya, melainkan dugaan korupsi yang membayangi relnya.
Publik menunggu langkah tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi yang muncul justru sikap pasif, seolah lembaga ini lupa pada mandat utamanya: membongkar kejahatan yang merugikan rakyat, bukan menunggu laporan.
Padahal, angka-angka yang terhampar di depan mata terlalu mencolok untuk diabaikan.
Biaya proyek Whoosh mencapai US$52 juta per kilometer, tiga kali lipat lebih mahal dari proyek sejenis di Tiongkok, yang hanya US$17–18 juta per kilometer.
Ekonom Anthony Budiawan menyebut selisih itu setara dengan kemahalan sekitar US$2,7 miliar: angka yang sulit dijelaskan dengan dalih teknis semata.
Kecurigaan publik kian kuat ketika diketahui bahwa bunga pinjaman dari Tiongkok mencapai 2 persen, atau dua puluh kali lipat lebih tinggi dibanding tawaran Jepang yang hanya 0,1 persen.
Lebih parah, pembengkakan biaya hingga US$1,2 miliar justru dibebankan kepada negara, bukan kontraktor.
Semua ini menunjukkan bahwa proyek ini sejak awal dirancang dengan logika politik, bukan ekonomi.
Dalam sistem yang sehat, kasus sebesar ini semestinya langsung diselidiki tanpa diminta.
Seperti dikatakan Boyamin Saiman dari MAKI, KPK seharusnya bersikap aktif, bukan “menunggu laporan seperti biro surat masuk.”
Undang-undang Pemberantasan Korupsi tidak memberi ruang untuk alasan “menunggu pelapor.” Ia justru mewajibkan tindakan proaktif terhadap setiap indikasi korupsi.
Namun KPK hari ini tampak kehilangan taringnya. Alih-alih menjadi lembaga superbody, ia kini lebih menyerupai lembaga superdiam.
Padahal, seperti pernah diingatkan Louis Brandeis, hakim agung Amerika Serikat, “Cahaya matahari adalah disinfektan terbaik, dan cahaya listrik adalah polisi paling efektif.”
Transparansi adalah obat paling ampuh terhadap korupsi. Tapi sinar itu kini padam, digantikan kabut kompromi dan ketakutan politik.
Kita tak bisa menutup mata terhadap fakta politik di balik proyek ini.
Mantan Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, adalah dua figur kunci dalam penentuan kerja sama dengan Tiongkok—dengan mengesampingkan tawaran Jepang yang lebih murah dan transparan.
Kini, ketika dugaan mark-up dan beban bunga menjerat negara, tanggung jawab politik keduanya tidak bisa dihapus begitu saja.
Dalam tradisi demokrasi yang sehat, mereka yang terlibat dalam proyek bermasalah seharusnya diperiksa secara terbuka dan independen. Bila memang bersih, proses itu akan mengembalikan kepercayaan publik.
Tetapi bila terbukti ada penyimpangan, penegakan hukum tak boleh berhenti di level teknis; ia harus menyentuh para pengambil keputusan tertinggi.
Seperti diingatkan John Adams, Presiden kedua Amerika Serikat, “Fakta adalah hal yang keras kepala; keinginan dan angan-angan kita tidak dapat mengubah kenyataan.” Fakta proyek Whoosh kini berdiri telanjang di depan rakyat.
Kita sedang dihadapkan pada ujian moral negara. Apakah hukum masih berlaku sama bagi semua, atau hanya bagi mereka yang tak berkuasa?
Bila KPK terus berdiam, sejarah akan menulis lembaga ini bukan sebagai pelindung publik, melainkan penjaga status quo.
Rakyat tidak butuh proyek megah yang dibangun di atas kebohongan. Yang dibutuhkan adalah negara yang jujur, yang berani memeriksa dirinya sendiri.
Korupsi bukan sekadar pencurian uang—ia adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Seperti dikatakan Nelson Mandela, “Ujian sejati dari integritas suatu bangsa bukan pada kemakmurannya, tetapi pada bagaimana ia menghadapi korupsi.”
Hari ini, ujian itu datang. Dan Indonesia harus memilih: berdiri di sisi kebenaran, atau tenggelam bersama proyek yang meluncur kencang menuju jurang ketidakadilan. ***